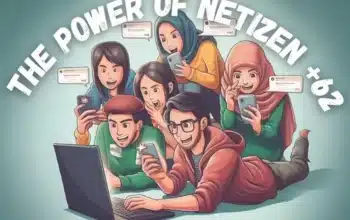Afrianto, M.Si (Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS)
Palopo, Wijatoluwu.com – Pilkada Palopo telah selesai. Naili dan Ahmad Syarifuddin Daud telah ditetapkan oleh KPU Kota Palopo sebagai pasangan calon terpilih, hasil dari proses demokrasi yang tidak mudah. Perjalanannya berat, penuh lika-liku, bahkan harus melewati penghitungan ulang. Tapi pada akhirnya, suara rakyat menemukan jalannya. Masyarakat yang sempat terbelah karena beda dukungan, mulai menarik napas panjang. Ada yang merasa menang, ada pula yang belajar menerima “kekalahan” dengan kepala tegak. Itulah wajah demokrasi: tidak selalu manis, tapi harus dijalani dengan lapang dada.
Tapi di tengah semua kepasifan saat ini, ada satu hal yang tak boleh ikut redup: janji-janji yang pernah dilontarkan. Janji bukan sekadar retorika di panggung kampanye. Ia adalah utang moril. Kontrak tak tertulis antara pemimpin dan rakyat. Kini, saat sorotan media mulai surut, justru di sinilah ujian sebenarnya dimulai. Bukan soal bagaimana mereka menang, tapi apa yang akan mereka lakukan setelah menang.
Saatnya yang terpilih merancang pembangunan 5 tahun ke depan dengan narasi teknokratik dan ilmiah. Slogan Naili–Ome yang pernah menggema di lorong-lorong kota: “Palopo Baru: Menuju Kota Jasa Global” perlu ditilik lebih dalam dengan berbagai pendekatan untuk memahami seperti apa kepentingan pembangunan yang akan dicapai.
Visi ini memang terlihat megah, penuh ambisi dan aspiratif, bahkan diklaim sebagai blueprint transformasi pembangunan perkotaan. Sebuah janji besar bahwa kota kecil di ujung timur Sulawesi Selatan ini akan bertransformasi dari kota kecil yang populasinya kurang lebih 200.000 jiwa menjadi service hub yang terhubung dengan jaringan ekonomi global. Lalu, muncul pertanyaan kritis:
Apakah kapasitas fiskal, institusional, dan struktural ekonomi Palopo saat ini cukup memadai untuk menopang impian sebesar itu?
Kalau kita baca dengan hati-hati, visi-misi yang dimuat pasangan Naili dan Akhmad Syarifuddin Daud ke KPU Kota Palopo sebenarnya bukan sekadar daftar janji politik yang biasa kita lihat saat musim kampanye, ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Mereka bicara tentang “Palopo Baru”, tapi bukan dalam arti menghancurkan semua yang lama dan memulai dari nol. Justru sebaliknya, mereka mengajak kita untuk melanjutkan yang baik, memperbaiki yang kurang pas, menghentikan yang salah, dan berani mencoba hal-hal baru. Itu artinya bahwa ada kebiasaan yang mesti diperbaiki, sistem yang diperhalus, dan kebijakan yang dievaluasi.
Terkadang, perseteruan politik menimbulkan sekat terak dan selalu membayangi dinamika kebijakan daerah. Tapi bukan berarti kita harus terjebak di situ. Kita bisa merubahnya, asal tahu dari mana kita mulai.
Namun, jika kita menelusuri dokumen ini dengan kacamata teknokratik, retakan dalam narasi mulai terlihat. Saskia Sassen dalam bukunya The Global City menyebutkan bahwa “Kota global bukan yang banyak dikunjungi turis asing, tapi yang punya kekuatan menggerakkan uang, informasi, dan keputusan dari jarak jauh. Kota-kota seperti Jakarta, Bangkok, maupun Tokyo bukan disebut global karena mereka memiliki gedung-gedung tinggi, punya banyak lampu jalan, tapi kota-kota ini punya jaringan ekonomi yang luas, sistem pemerintahan yang efisien, dan akses ke pasar global.”
Palopo jelas belum di sana, dan itu tidak masalah, karena tidak semua kota harus jadi global. Tapi masalahnya muncul ketika kita memakai istilah itu tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Mau jadi Kota Jasa? Boleh. Tapi jasa untuk siapa? Dengan infrastruktur digital seperti apa? Bagaimana akses ke pasar internasional? Apakah pelaku UMKM punya standar sertifikasi, logistik ekspor, atau jaringan distribusi global?
Jangan sampai ini menjadi ilusi pembangunan: janjinya megah tapi hanya menyisakan gedung kosong dan utang daerah yang menumpuk. Seperti yang diteliti oleh UN-Habitat yang berjudul Urbanization and Development in Southeast Asia: Regional Trends, Emerging Challenges (2022), ada bahaya tersembunyi dalam tren ini, yakni apa yang mereka sebut sebagai aspiration without capacity.
Lebih jauh, arsitektur kebijakan yang ditawarkan dengan mendorong 4 misi, 10 arah baru, dan 25 kegiatan unggulan memang terlihat sistematis. Namun, sistematis bukan berarti itu strategis. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan ke depan, setiap program harus lahir dari analisis kebutuhan, pemetaan kapasitas, dan evaluasi prioritas yang tentu saja tidak terpisah dari kepentingan pembangunan nasional dan regional. Pendekatan seperti ini yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan empiris masyarakat, bukan malah didorong oleh simbolisme kalender.
Dari sisi teknokratik, dokumen visi, misi, dan program ini diharapkan memiliki baseline data, target, dan mekanisme evaluasi independen agar program ini tidak saja menghasilkan output, tetapi lebih jauh pada outcome-driven. Artinya, program-program pembangunan yang dikerjakan tidak sekedar menghitung seberapa banyak uang yang dibelanjakan, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.
Namun, ada hal lain yang perlu dicermati terkait kemampuan keuangan daerah. Jika kita menguraikan kebutuhan belanja semua program seperti pembangunan rumah sakit jiwa, pembangunan kolam retensi, pengadaan seragam gratis, bantuan maksimal Rp1 miliar setiap kelurahan, menaikkan TPP tiap tahun, dan program lainnya, membutuhkan anggaran hampir 55% dari APBD. Ini belum termasuk belanja barang dan jasa di kisaran Rp360-an miliar, belanja pegawai sekitar Rp515 miliar per tahun. Sementara APBD Palopo hanya berkisar Rp1 triliun. Bahkan terdapat pembayaran cicilan pokok utang, bunga utang, dan utang belanja lainnya.
Lalu, di mana letak fiscal sustainability-nya? Apakah akan mengandalkan hibah pusat, KPBU, atau pinjaman daerah yang berisiko menjerat Palopo dalam krisis utang besar?
Situasi ini memang menyulitkan bagi pemda ke depan untuk mengakselerasi pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah yang rendah. Lalu, apakah ini punya korelasi kuat untuk meningkatkan PAD dua kali lipat sebagaimana dalam janji politiknya yang tertuang di poin 19, dengan melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi melalui pemanfaatan aset?
Meskipun niatnya mulia, program ini perlu diwaspadai karena “optimalisasi pajak” sering kali berujung pada pembebanan berlebihan kepada rakyat kecil, sementara pelaku usaha besar atau elit lokal bisa lolos.
Dan yang paling mengganjal dari dokumen program ini adalah kenaikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tiap tahun, di mana desain strategi pelaksananya juga dikaitkan dengan “peningkatan PAD”. Artinya, ada logika tersembunyi: “Kita naikkan pajak, supaya bisa naikkan gaji pegawai.” Bukan salah, tapi ini sangat berisiko. Karena jika prioritas utama PAD adalah untuk membiayai belanja pegawai, maka rakyat bukan jadi tujuan, melainkan sumber pembiayaan.
Padahal, idealnya, PAD itu seperti air hujan: dikumpulkan dari mana-mana, tapi dikembalikan dalam bentuk sumur yang jernih, jalan yang tidak berlubang, sekolah yang layak, dan pasar yang rapi. Bukan untuk menutupi defisit anggaran atau menaikkan gaji aparatur tanpa kaitan langsung dengan pelayanan publik.
Bukan berarti tidak ada harapan. Dalam dokumen ini, kita masih punya optimisme dari kebijakan yang potensial. Program ekonomi hijau dan biru sebagai salah satu pilihan strategis yang sangat relevan bagi kota pesisir dengan panjang garis pantai 21 km, revitalisasi Istana Kedatuan Luwu, dan penataan kampung tematik bisa menjadi daya tarik pariwisata dan investasi. Tentu saja jika ini dikembangkan secara serius, bisa menjadi niche komparatif Palopo.
Tapi lagi-lagi, ini soal paradigma, tata kelola yang transparan, anggaran yang realistis, dan kapasitas birokrasi yang mumpuni, serta kemauan pengambil kebijakan di kota.
Kota Palopo bukan Jakarta, bukan pula seperti Makassar. Palopo adalah kota menengah dengan sumber daya yang terbatas. Maka, yang dibutuhkan bukanlah visi yang terlalu tinggi hingga tak menyentuh tanah, melainkan strategi yang visioner sekaligus realistis. Kota Palopo bisa menjadi baru, bukan karena ingin ditampilkan seperti kota besar, tetapi dibangun dari realitasnya sendiri. Di mana semua warga berharap kota kecil yang adil, lestari, dan bermartabat. Dan itu, justru, adalah bentuk globalisasi yang paling autentik.